Petualanganmu di dunia ini telah berakhir. Tepatnya Rabu malam, 13 Agustus 2025, di RS Primaya Makassar, tempat yang sama sekali tidak mencerminkan keagungan pikiran yang selama ini kau semaikan. Tapi mungkin memang begini takdir seorang pencerah—ia tidak memerlukan panggung megah untuk menyelesaikan misinya di dunia. Yang ia butuhkan hanyalah senyum, salam, dan ketulusan hati seperti yang selalu kau tawarkan kepada setiap orang yang berpapasan denganmu. Ya, itulah definisi sejati seorang pencerah—tidak pernah padam meski badai menghadang, terus belajar meski ajal mulai mendekat.
Saya mendengar kabar tentang kepergianmu saat saya masih berada di kaki gunung Tambora, Dompu, Nusa Tenggara Barat, berjarak ribuan kilometer jauhnya dari Kota Makassar. Lalu terbayang serpihan serpihan pertemuan, meski tidak begitu intens seperti sahabat lainnya yang mengenalmu. Saya adalah mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin dan engkau mengajar di tetangga sebelah, Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya justru baru mulai tertarik mengenal namamu lewat almarhumah istri saya, Uci, mantan ketua Kornas Kohati HMI MPO. Lewat beliaulah saya mulai menapaki labirin gagasanmu yang bertebaran di kolom-kolom koran dan panggung-panggung seminar.
Hal pertama yang pertama kali hadir adalah gambaran wajahmu di koridor kampus Unhas, sebuah senyum yang selalu tersungging, lebih dulu menawarkan persahabatan. Senyum itu adalah pembuka dari segalanya. Lalu, akan terdengar suaramu yang teduh, mengucap, “Assalamualaikum.” Salam yang bukan sekadar sapaan, melainkan doa yang kau tebarkan kepada siapa pun yang kau temui. Setelahnya, menyusul pertanyaan sederhana itu, “Apa kabar?” Mungkin bagi orang lain itu terdengar seperti basa-basi belaka, sebuah formalitas sosial yang diucapkan tanpa makna. Tapi kami yang mengenalmu tahu, pertanyaan itu adalah caramu mengulurkan sebuah jembatan, sebuah undangan tulus untuk sebuah persahabatan yang hangat. Dalam tiga kata itu, terkandung sebuah kepedulian otentik.
Kehangatan itu pula yang kau bawa ke dalam ruang ruang kuliah dan di manapun. Bagimu, mengajar adalah sebuah ajakan untuk berpetualang bersama, untuk menyelami lautan makna di era digital yang semakin riuh dan kompleks. Engkau bukan sekadar dosen. Tapi juga seorang mentor. Kehangatan persahabatan yang kau tawarkan bak mata air yang memancar dari hati yang tulus, mengalir dan menyirami jiwa-jiwa generasi muda yang sedang tumbuh. Namamu harum bahkan di antara para demonstran.
Ada satu kisah, saat engkau masih menjabat sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan, terjadi penutupan jalan oleh demonstran di depan Kampus Universitas 45, Makassar yang membuatmu terhalang menghadiri undangan rapat Gubernur Sulsel untuk persiapan Muktamar Nadhlatul Ulama (NU).
Para mahasiswa hendak menyandera semua yang berplat merah. Aksi ini sebagai simbol kemarahan mahasiswa terhadap pemerintahan SBY-Boediono yang dinilai terlibat dalam skandal Bank Century. Kebetulan mobil kijang yang engkau tumpangi juga berplat merah.
Melihat keadaan ini, engkau tidak gentar, malah mencoba menyapa para demonstran. Engkau pun membuka kaca pintu mobilmu lalu berujar, “Hidup mahasiswa!” Ucapanmu itu serta merta membuat mahasiswa balik sadar siapa sosok di hadapan mereka. Mereka pun meminta maaf. Bahkan badan jalan yang tadinya tertutup segera dibuka dan mempersilakan agar mobilmu bisa bergerak dengan lancar.
“Mungkin ini hikmahnya kalau pejabat juga aktivis dan sering menghadiri acara-acara yang digelar mahasiswa,” tuturmu kepada mahasiswa seperti yang dituliskan Jumadi Mappanganro, reporter Tribun Timur saat itu.
Engkau lahir di tanah yang subur dengan tradisi keilmuan, Palopo tahun 1963. Sepertinya tanah itulah yang membentuk karaktermu—tenang tapi dalam, hangat tapi bijaksana. Kau membangun fondasi keilmuanmu dengan sabar. Engkau pun tidak pernah berhenti belajar. Hingga akhir hayatmu, engkau tetap mendudukkan dirimu sebagai seorang murid yang haus akan pengetahuan, meski orang orang menyebutmu guru.
Engkau adalah perwujudan dari seorang intelektual yang konsisten, seorang pembaca dan penulis yang istiqomah. Aku membayangkan tumpukan buku yang memenuhi ruang kerjamu, selalu bertambah. Bagimu, belajar adalah perjalanan seumur hidup, sebuah napas yang tak boleh berhenti hingga akhir hayat. Dan dari proses membaca yang tak kenal lelah itulah lahir tulisan-tulisanmu yang mencerahkan.
Di Harian Fajar engkau menyajikan “Secangkir Teh” kolom tetapmu yang ditunggu pembaca sebagai santapan rohani; ide-ide yang sarat dengan perenungan yang mendalam, menggugah, dan memaksa pembaca untuk berpikir kritis. Engkau membawa ilmu komunikasi keluar dari kungkungan teori yang kaku dan menyajikannya sebagai alat bedah untuk menganalisis realitas sosial dan politik.
Bahkan di saat-saat terakhirmu, ketika raga tak lagi sekuat dulu dan rasa sakit mulai membatasi gerak, engkau terus memaksakan diri menumpahkan ide, sebuah kegelisahan yang tak bisa kau bendung. Sebab bagimu, menulis untuk mencerahkan umat adalah sebuah kewajiban suci, sebuah panggilan jiwa. Di situlah puncak dari ke-istiqomah-anmu. Di tengah kelemahan fisik, semangat intelektualmu justru menyala semakin terang, membuktikan bahwa api pengetahuan memang tak boleh padam oleh badai apa pun.
Dedikasimu pada pencerahan publik juga terwujud dalam pengabdianmu di berbagai lembaga. Selain pernah menjabat sebagai Ketua KPID Sulawesi Selatan, engkau juga diberi amanah sebagai Ketua Komisi Informasi Sulsel, hingga menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Di setiap posisi itu, misimu selalu sama dan tak pernah berubah: memperjuangkan hadirnya sebuah tatanan informasi dan penyiaran yang sehat, harmonis, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur demokrasi. Engkau adalah penjaga frekuensi publik, memastikan bahwa gelombang udara selalu terisi dengan konten yang mendidik, bukan yang merusak.
Di balik citra akademisi yang serius dan intelektual publik yang kritis, ada sisi lain dirimu yang menunjukkan keluasan minat dan kedalaman jiwamu. Selain aktif di Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dan Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), yang paling unik adalah ketika engkau mendirikan komunitas Liga Film Makassar. Ini adalah bukti nyata bahwa pemikiran kritis bisa dan harus diterapkan di semua aspek kehidupan, bahkan dalam hiburan sekalipun.
Dan atas semua peran yang kau jalani itu, engkau adalah seorang hamba yang tulus. Di Masjid Al Markaz Al Islami, saat saya mulai merintis penerbitan Buletin GAMIS (Gema Al-Markaz Al Islami) bersama almarhum Anwar Halim, sekali dua kali kita berjumpa, saat engkau hendak melaksanakan sholat. Pastilah bukan di masjid itu saja engkau alirkan pesan pesan dakwahmu yang dikenal jauh dari kesan menggurui atau menghakimi. Sebaliknya, merangkul dan mengajak.
Lisanmu menyejukkan, tulisanmu menggerakkan. Engkau mengajarkan bahwa kata-kata yang lahir dari hati akan selalu menemukan jalannya untuk sampai ke hati yang lain. Kelembutan dakwahmu adalah cerminan dari kehangatan pribadimu, yang selalu dimulai dengan senyum, salam, dan pertanyaan tulus tentang kabar. “Assalamu alaikum, apa kabar?”
Kini, engkau telah pergi, memulai perjalanan panjangmu yang abadi. Engkau meninggalkan sebuah kekosongan dalam dunia intelektual. Setiap kalimat yang pernah kau tulis, setiap nasihat yang pernah kau berikan, setiap senyum yang pernah kau tebarkan, adalah jejak abadi yang tak akan lekang oleh waktu. Engkau telah menunjukkan kepada kami semua bahwa seorang intelektual sejati tidak bisa hidup sendirian di menara gadingnya. Ia harus turun ke jalan, berbagi pengetahuan, mencerahkan umat, dan menjadi jembatan antara dunia akademik dengan realitas sosial yang sesungguhnya.
Warisan terbesarmu bukanlah gelar atau jabatan yang pernah tersemat di namamu, melainkan ketulusan untuk berbagi, dan keberanian untuk berpikir. Di era di mana informasi begitu melimpah namun kebenaran terasa semakin kabur, sosok sepertimu adalah kompas, pengingat akan pentingnya integritas intelektual dan tanggung jawab moral seorang pendidik.
Kini engkau pamit. Warisan pemikiranmu, kehangatanmu, dan istiqomahmu dalam belajar akan menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Suguhan “Secangkir Teh” terakhir yang dimuat di Harian Fajar, Jumat 8 Agustus 2025 berjudul “Bendera One Piece di HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Simbol Kritik atas Kegagalan?” selamanya akan menjadi epitaf intelektual yang indah bagi pembaca kritis:
…Menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ruang publik dan digital kita disuguhi peristiwa menggelitik sekaligus menyentil nurani kebangsaan kita. Di beberapa tempat, bendera bergambar tengkorak khas bajak laut dari serial One Piece—Jolly Roger—berkibar bersamaan dengan Sang Saka Merah Putih. Sekilas ini tampak sebagai ulah remaja yang salah kaprah, namun jika direnungkan lebih dalam, ini menyimpan luka simbolik sekaligus kritik sosial yang tidak bisa diremehkan…
Untuk memahami teks di atas, perlu pemahaman lebih jauh ke dalam semesta One Piece itu sendiri. Generasi muda Indonesia yang mengibarkan bendera ini, sadar atau tidak, mereka sedang melakukan sebuah transposisi simbolik. Mereka memproyeksikan kekecewaan terhadap realitas bangsa saat ini. Pemerintah Dunia (World Government) yang sewenang-wenang –sebagaimana digambarkan dalam narasi fiksi tersebut– mereka juga saksikan dalam praktik-praktik kekuasaan di negeri ini yang kerap abai pada suara rakyat. Para elite politik dan ekonomi yang hidup dalam gelembung privilese, berjarak jauh dari penderitaan rakyat jelata. Janji-janji kemerdekaan yang termaktub dalam konstitusi—keadilan sosial, kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa—terasa seperti sebuah utopia yang terus dibicarakan, dikejar, namun tak kunjung ditemukan.
Ini adalah bentuk kritik yang paling subtil sekaligus paling menohok. Tidak lagi menggunakan bahasa formal ala aktivis ’98 atau jargon-jargon kiri yang usang, melainkan medium yang paling akrab dengan dunia anak muda saat ini: meme, simbol budaya pop, dan parodi. Kritik ini lahir dari sebuah malaise, sebuah kegelisahan mendalam atas retaknya kontrak sosial antara negara dan warga negara. Negara, yang seharusnya menjadi rumah bersama, dianggap gagal memberikan rasa aman, keadilan, dan harapan.
Fenomena ini menandai sebuah pergeseran tektonik dalam lanskap kritik sosial di Indonesia. Jika dulu kritik mengalir deras dari kampus, serikat buruh, atau lembaga swadaya masyarakat, kini ia bermetamorfosis menjadi desentralisasi dan terfragmentasi di ruang-ruang digital. Agora baru telah lahir: media sosial. Di sinilah diskursus kebangsaan dibentuk, diperdebatkan, dan sering kali direduksi menjadi perang tagar dan pertarungan para buzzer.
Di tengah hiruk pikuk seperti inilah, kami para pembaca semakin merindukan sosok seperti dirimu yang teguh melahirkan kritik lewat tulisan-tulisan bernas. Engkau menumbuhkan tradisi intelektual yang kini kian tergerus: tradisi kritik dengan argumentasi yang kokoh, dan yang terpenting, empati kemanusiaan. Kritik yang kau sampaikan melalui tulisan-tulisanmu tidak pernah bertujuan untuk menghakimi atau merendahkan, melainkan untuk mengajak berpikir, untuk merenung bersama. Engkau adalah seorang pencerah dalam arti sesungguhnya—membukakan jendela-jendela baru agar kita semua bisa melihat cakrawala yang lebih luas, bukan sekadar menyalahkan kegelapan di dalam ruangan.
Engkau melihat sebuah bangsa yang secara ritualistik merayakan kemerdekaannya setiap tahun dengan gegap gempita, namun di saat yang sama, nilai-nilai kemerdekaan itu sendiri—kebebasan berpendapat, kesetaraan di hadapan hukum, keadilan ekonomi—terus-menerus digerogoti dari dalam.
Perilaku para elite yang mengelola negara justru kerap mempertontonkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang paling memuakkan. Terjadi sebuah proses yang oleh para filsuf disebut sebagai desakralisasi simbol: ketika makna luhur sebuah simbol terkikis habis oleh realitas yang mengkhianatinya.
Saya tahu, engkau pasti kecewa melihat potret kontradiktif ini: sebuah generasi baru yang tumbuh dengan referensi global, yang mendamba kebebasan dan keadilan universal, namun terpaksa berhadapan dengan sebuah sistem yang feodalistik, birokratis, dan seringkali anti-kritik. Kekecewaanmu ini bukanlah pengkhianatan terhadap bangsa. Sebaliknya, sebentuk cinta yang terluka. Kritik yang lahir dari hatimu yang peduli karena menginginkan Indonesia menjadi lebih baik, ke arah cita-cita kemerdekaan yang sejati.
Seperti itulah engkau menandai dirimu.
Sebelum engkau pergi, engkau serahkan sebuah cermin besar yang kau letakkan di hadapan kami semua, “Hendak kemana bangsa ini?”
Tambora, 17 Agustus 2025
Penulis : Muhary Wahyu Nurba
Editor : Wahyu J.Ibrahim















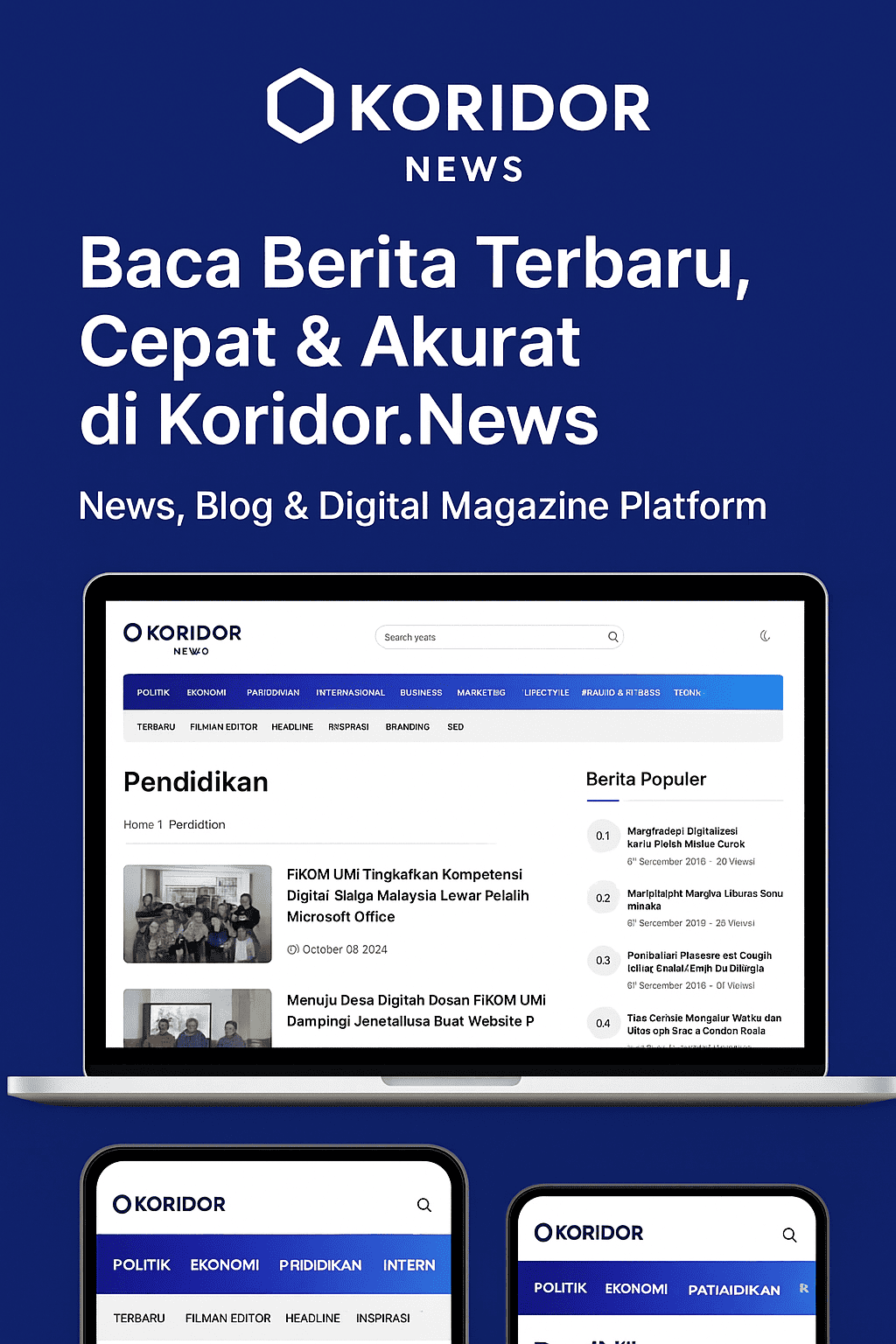
Comment